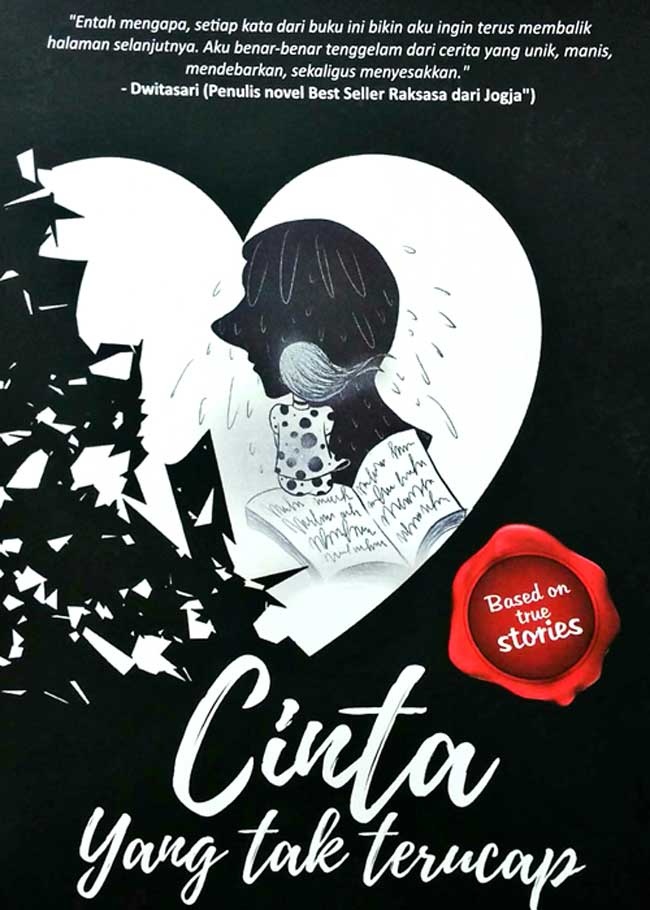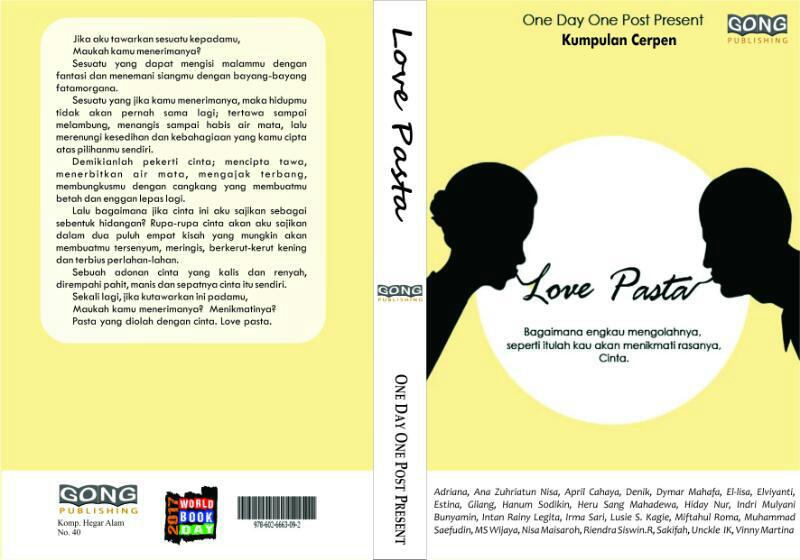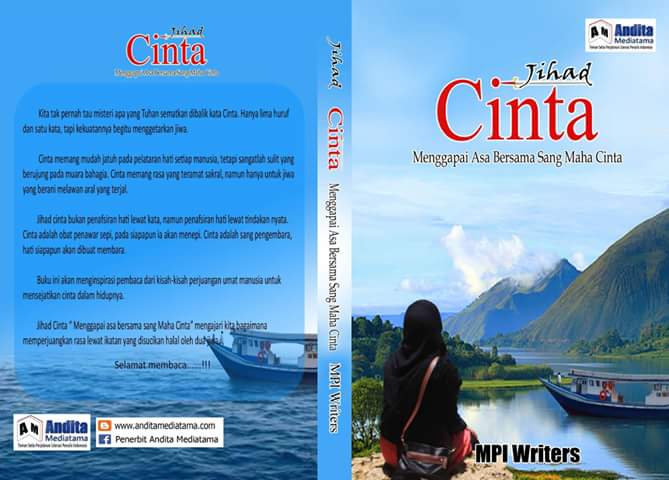Hujan tak kunjung berhenti mengguyur Anjuk Ladang,
kota kecil yang berada di kaki gunung Wilis. Setelah beberapa hari tirta
cakrawala enggan membasahi bumi, malam itu dia seperti membayar lunas tugasnya
yang tertunda.
Hingga tengah malam, langit masih gelap gulita. Kudongakkan kepala ke atas. Tak tampak sebuah bintangpun berkelip di sana.
Padahal, seharusnya rembulan bersolek dengan bentuk sempurna di angkasa.
Iya, malam itu adalah malam kelima belas dalam
penanggalan Jawa. Malam purnama, dimana di pendopo kabupaten Nganjuk selalu terlihat
kesibukan puluhan orang yang menjadi pengabdi seni. Mencurahkan hidupnya untuk
berbhakti, demi lestarinya peninggalan adiluhung moyang kami.
“Ayo bangun, waktunya pulang,” samar-samar
kudengar suara itu. Sedikit tergesa-gesa, tanganku digandengnya.
Dengan kantuk yang masih membekap dua kelopak
mata, antara sadar dan tidak, aku bisa melihat orang-orang tampak bergegas
meninggalkan pendopo. Sebagian berlari kecil menghindari guyuran gerimis.
Beberapa menit sesudahnya, beberapa di antara mereka telah mengayuh sepeda
onthel, melintas di depan kami sambil melambaikan tangan. Lalu melempar senyum yang
bersahabat.
“Pareng, Bu.
Kulo rumiyin ---- Mari, Bu. Saya duluan,” sapa mereka.
“Monggo ---- silahkan,”
jawab wanita yang disapa.
“Ayo, itu Kang Man sudah datang,” lagi-lagi
tanganku digandeng. Di depan pagar kantor kabupaten, seorang tukang becak ----- sebutan abang
becak di kota asal saya ----- langganan meminggirkan kuda besi tua.
Iya, hampir setiap kamis malam, dan malam kelima
belas dalam kalender Jawa, si tukang becak itu selalu menjadi langganan sang
biduan. Mengantar dan menjemput dari rumahnya yang berada di pelosok desa, jauh
dari pusat kota, menuju pendopo yang tepat berada di samping alun-alun Nganjuk.
Sebuah paguyuban karawitan rutin pentas di sana. Biasanya
disiarkan langsung oleh Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Nganjuk. Meski
tak banyak yang mendengarkan siaran itu mungkin. Pada hari tertentu, mereka akan mengundang
seorang dalang untuk wayangan.
Malam itu, sepanjang perjalanan dari pendopo menuju rumah,
sang biduan tiada henti-hentinya menasehatiku.
“Mbésok, ojo
dadi wong sêni. Dadio wong pintêr. Ndang oncat saka kutha kéné. Golèko penggawèyan sing bisa kanggo nguripi anak lan bojomu ---- Kelak, jangan
berprofesi sebagai seniman. Jadilah orang pintar. Merantaulah dari kota ini. Cari
pekerjaan layak yang bisa kamu gunakan untuk menafkahi anak dan istrimu,”
tuturnya.
“Nggih
---- Iya,” jawabku singkat.
Kalimat yang terlontar dari sang biduan bukan
tanpa alasan. Kehidupan seniman pinggiran, apalagi kelas kampung, penuh dengan
kesusahan. Dalam hal penghasilan tentunya. Untuk sebuah pengabdian seni seperti
malam itu, uang yang dia terima hanya cukup dipakai membeli beberapa kilo beras
besok pagi. Sedangkan lauk pauknya, biasanya masih harus menghutang di toko pracangan ----- sembako ---- Yu Dami. Seorang
taipan Jawa yang galaknya bukan kepalang saat menagih hutang.
Hidup dengan segala keterbatasan seperti itu sudah mendarah daging dalam keseharian sang biduan. Tetapi, semua tetap dia
jalani tanpa berniat sedikitpun untuk berhenti dari me-nyinden ---- mendendangkan tembang Jawa. Menjual lantunan
suara dari panggung ke panggung, mengais remahan rejeki dari sana. Jangan harap
akan ada pundi-pundi uang berlebih.
Bagi sang biduan, ada nilai yang tak bisa dihargai dengan materi. Menjaga seni dan budaya agar tetap terpelihara. Itulah
misi sejati dia.
Belasan tahun aku melewati malam-malam seperti itu bersama sang biduan.
Terkadang harus ikut berbasah kuyup saat hujan, karena
plastik penutup becak milik Kang Man sudah compang-camping. Berlubang di
sana-sini. Tak jarang pula menunggu berjam-jam, mencari tukang becak lain yang
melintas depan pagar pendopo kabupaten, ketika becak langganan kami berhalangan.
Tiba-tiba rasa kantuk yang tadi menyelimuti kedua
kelopak mataku telah sirna. Tujuh kilo dari pusat kota, jalan yang kami lalui
mulai membelah hamparan sawah. Gerimis sudah tak lagi turun.
Sepanjang kanan kiri jalan, kawanan kodok ijo ----- katak hijau (fejervarya cancrivora) terdengar merdu
bersahut-sahutan. Pertanda hujan sudah benar-benar reda. Dari kejauhan, terlihat
sorot lampu para tukang suluh kodok
----- pemburu katak sawah ----- mulai berkilatan. Cuaca seperti ini, bagi
mereka adalah berkah tiada tara. Bisa dipastikan, hasil buruan mereka akan
melimpah.
Sungguh, Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, Allah SWT
senantiasa memberi banyak pintu rejeki bagi manusia yang mau berusaha dan
bekerja.
Akhirnya, kami mulai memasuki gapura desa. Tak
lama berselang, Kang Man yang sudah hapal dengan tujuan, menghentikan becaknya
tepat di sebuah rumah tanpa pagar dan hanya berlantai tanah.
“Matur suwun
---- terima kasih, Bu,” ucap Kang Man ketika menerima selembar uang sepuluh
ribuan yang diulurkan sang biduan.
Tukang becak itu sempat mengusap kepalaku, sebelum
akhirnya memutar haluan dan kembali mengayuh kuda besi tua miliknya. Sementara
sang biduan sibuk membuka kunci pintu rumahnya. Aku masih diam berdiri di tengah
halaman.
Kembali kudongakkan kepala ke atas cakrawala. Terlihat
sebuah bintang yang bersinar terang di sana.
Lintang
Panjerwengi. Bintang Alpha Centauri.
"Ah, alangkah indahnya malam ini," gumamku dalam batin.
-o0o-
Tiga dasawarsa telah berlalu.
Kini, sang biduan
sudah tidak lagi menjual lantunan suaranya. Paguyuban-paguyuban karawitan dan
para dalang wayang sekarang lebih tertarik untuk menggunakan jasa biduan-biduan
muda. Meninggalkan sinden-sinden pinggiran kelas kampung yang semakin renta.
Sebagai gantinya, untuk menafkahi hidup sang
biduan, setiap minggu aku rutin menyisihkan sebagian rejeki, lalu mengirimkan kepadanya.
Sebagai pengingat atas perjalanan membahagiakan setiap kamis malam di masa
kecil dulu. Pengganti sepiring nasi rawon yang selalu kuterima dari pramu saji ---- pelayan ---- pendopo kabupaten saat
manggung di sana.
Semoga sang biduan senantiasa dikarunia kesehatan
dan umur panjang.
Doakan juga aku tetap sehat, agar bisa terus bekerja. Demi
menafkahi orang-orang tercinta. Istri, anak, dan tentunya sang biduan.
Aamiin Ya Robbal Alaamiin.
Ayu, Hayu
Rahayu Wilujeng.
Heru
Sang Mahadewa
Member of #OneDayOnePost
Catatan:
Tulisan ini saya dedikasikan untuk Ibu Siti
Fatimah (nama udara pemberian Pak Gondo Sutrisno, penyiar RKPD Nganjuk), seorang
sinden kabupaten ----- sebutan untuk
biduan Jawa ----- di tahun 90-an yang biasa mengiringi pentas sebuah paguyuban karawitan binaan
Pemda.
Sang
biduan Jawa itu adalah ibu saya.
 |
| Sang biduan di masa muda, bersama Lik Karsih yang juga biduan |
 |
| Sang biduan Jawa |