Berbeda
dengan kereta di arcapada yang lazim ditarik sepasang kuda, kereta kencana yang membawa Puntadewa dari
gerbang Indrabhawana menuju swarga ditarik oleh seekor gajah putih bernama Airawata. Ia adalah gajah penghuni Kahyangan Tejamaya. Kahyangan yang menjadi kedhaton
Bhatara Indra.
Rupanya kedatangan Puntadewa telah ditunggu oleh Bhatara Narada di swarga. Turun dari kereta kencana, ia diajak menyusuri jalan yang dipenuhi kembang beraneka warna. Aroma harum tumbuhan swarga berkelindaran di udara.
Mata
Puntadewa terbelalak, manakala melewati sebuah persimpangan, ia menangkap
pemandangan menakjubkan. Sebuah puri berdiri kokoh, lengkap dengan Bale Witana. Di dalam wandapa yang lebih megah dari kedhaton
Hastina dan Amarta itu, nampak sesosok manusia sedang duduk di atas singgasana
bertahta emas. Tak jauh dari palinggih raja, pada hamparan meja besar, teronggok
berlimpahnya makanan dan minuman nan lezat.
Serta
merta Puntadewa menelan ludah. Jika ingatannya tidak memudar, sudah delapan
puluh hari delapan puluh malam, semenjak berangkat dari Hastina menuju puncak
gunung Jamurdipa, ia menjalani tirakat. Lahir maupun batin. Naluri dahaga manusiawinya
terpantik seketika. Tetapi buru-buru lenyap, manakala ia bisa mengenali sosok
yang ada di dalam puri. Sosok yang tak asing baginya.
Duryodhana?
Nama
itu terlontar dari bibir Puntadewa. Iya, ia memang bisa melihat dengan jelas,
Duryodhana sedang duduk dikelilingi banyak perempuan cantik. Bidadari tentunya, pikir Puntadewa.
Kenapa Duryodhana yang beperingai angkara
murka, yang telah menabrak segala pagar batas kebolehan mengusik saudara,
bahkan telah terang-terangan memutus dadung kerukunan wangsa Bharata untuk meuaskan
ambisi duniawinya, sekarang justru duduk di singgasana itu dengan bergelimang
kebahagiaan?
Pertanyaan-pertanyaan
itu terus membuncah di dada Puntadewa.
“Aku tahu, apa yang sedang bergelayut di pikiranmu, kulup. Di swarga, tidak ada perbedaan siapa pemenang dan siapa yang
kalah pada Bharatayuda. Setiap manusia yang telah menjalankan dharma sebagai
kesatria Kuru Setra, akan diangkat derajatnya. Mereka berhak hidup kekal di
sini.”
Bathara
Narada mengelus dagunya yang ditumbuhi jenggot ubanan.
Puntadewa
mengangkat sembah, “Hamba, pukulun.
Apakah Kurawa pantas disebut sebagai kesatria?”
“Duryodhana
dengan gagah berani telah mampu mencapai tingkatan itu karena dharma kesatriaanya,
meskipun dia berada di pihak Kurawa. Pihak yang menurut sudut pandang manusia
mewakili watak angkara.”
Untuk
kedua kalinya, Puntadewa menyembah. “Jika demikian, kenapa Dewata membiarkan Bharatayuda pecah? Kenapa darah sesama wangsa Bharata harus saling
ditumpahkan?”
“Bharatayuda
bukan sekedar perang antara dharma melawan angkara. Tetapi ia adalah inti dari
perjalanan hidup manusia itu sendiri.” Bhatara Narada melanjutkan pituturnya, “Tinggallah
di sini, kulup.”
Puntadewa
tidak serta merta bisa menerima penjelasan Bhatara Narada. “Lalu, di mana
sekarang istriku dan empat putra ramanda Pandu lainnya?”
“Drupadi,
Wrêkudhara, Arjuna, Nakula, dan Sadewa sedang menjalani pembersihan jiwa atas
dosa-dosa mereka selama menjalankan dharma di arcapada, kulup.”
“Hamba,
pukulun. Tiada sejengkalpun tanah di swarga ini yang pantas hamba pijak, jika hamba tidak bersama mereka.”
Bhatara
Narada mengangguk-angguk, lalu menebar senyuman ke arah Puntadewa.
“Baiklah.
Kulup Puntadewa akan diantar Dewata untuk menemui mereka.”
Sekedipan
mata kemudian, sosok Dewata bertubuh tambun itu berlalu dari hadapan Puntadewa.
Kecepatan langkahnya bagai laju sinar bagaskara. Indera penglihatan Puntadewa
tak mampu mengikutinya. Bhatara Narada seolah lenyap begitu saja.
-oo0oo-
Tak
jauh dari sebatang pohon waringin, Puntadewa duduk sedemikian rupa hingga tubuhnya
sempurna membentuk posisi siddhasana.
Sementara, kedua telapak tangan putra tertua Prabhu Pandu itu tertangkup rapat
dalam sikap Anjali Murda.
Dalam
hitungan lima, sepuluh, dua puluh, dan tiga puluh hembusan napas kemudian,
suksma Puntadewa kembali melesat meninggalkan alam kasunyatan.
Berbeda
dengan perjalanan sebelumnya, kali ini Puntadewa disuguhi pemandangan yang sangat mengerikan. Jalan
yang ia lalui bukan hanya licin dan sempit, namun juga gelap gulita tanpa
sepercik cahaya pun. Hanya sesekali saja, dari ujung yang entah seberapa
jauhnya, terlihat kilatan dari nyala api. Bau busuk yang lebih busuk dari
bangkai juga menghajar indera penciumannya.
Puntadewa
nyaris tidak mampu melihat apa-apa. Ia hanya mengandalkan kedua tangannya yang
meraba-raba tebing di sisi jalan. Semakin lama ia berjalan, bau
busuk kian menusuk hidungnya.
Setelah merayap sekian lama, Puntadewa sampai di ujung kegelapan. Di hadapannya terpampang sebuah mulut goa, di
mana kobaran api yang seram menjilat-jilat seluruh ruangan dalam goa.
Puntadewa
mundur beberapa langkah, manakala di balik benderangnya nyala api, matanya
menangkap pemandangan yang memilukan. Bangkai-bangkai hewan bertumpang tindihan
dengan mayat manusia di sana. Sebagian dari mayat-mayat itu, hanya tinggal
tempurungnya. Sebagian lagi memamerkan isi perut yang terburai.
Mendadak
terdengar jeritan dari balik kobaran api yang menyeramkan itu, “Samiaji …
Samiaji … Samiaji!”
Puntadewa
mencoba memasang indera pendengarannya lebih tajam. Samiaji adalah nama
kecilnya. Siapa gerangan yang
memanggilku?
“Tolonglah kami. Kehadiranmu telah mampu membuat derita kami berkurang. Lihatlah, Samiaji.
Siksa yang kami jalani ini mendadak terhenti.”
Suara-suara
itu terdengar bukan hanya satu orang. Tetapi ia diteriakkan oleh beberapa orang yang terus
bersahut-sahutan.
Lambat
laun, ingatan Puntadewa bisa menangkap bahwa suara itu adalah milik Drupadi,
Wrêkudhara, Arjuna, Nakula, dan sadewa.
Seketika,
Puntadewa menjerit!
Batinnya
memberontak. Dharma hidup macam apakah yang ia jalani selama ini?
Bagaimana
mungkin, Drupadi dan Pandawa yang senantiasa menjalani tirakat, mendekatkan diri kepada Sang Maha Suci sepanjang hidup mereka, justru berakhir
di neraka?
Dalam
puncak ketidakterimaan atas pemandangan yang terpampang di hadapannya, Puntadewa meratap, “Jagad
Dewa Bhatara, jika semua dharma selama hidup hamba bisa
menggantikan mereka di neraka, biarlah hamba yang menjalani siksaan. Angkatlah
mereka dari penderitaan ini.”
Tubuh Puntadewa terjatuh dalam posisi bersimpuh.
“Bangunlah,
kulup.”
Sebuah
tepukan di pundak, membangunkan Puntadewa dari samadhi. Ketika membuka mata, ia
melihat Bhatara Yama, Bhatara Indra, dan Bhatara Narada telah berdiri di
hadapannya. Samar-samar, ia juga mencium semerbak aroma harum yang tertebar dari tempat di
sekelilingnya.
“Ketahuilah,
kulup. Ada waktu, di mana perjalanan suksma para kesatria yang telah mokta,
harus merasakan penderitaan dan siksaan beberapa saat di neraka. Itulah yang
sedang kulup lihat atas semua yang dialami Kurawa di swarga, juga Pandawa di
neraka.”
Bhatara
Narada kembali bertutur. Yang diajak bicara hanya menghela napas panjang,
sembari mengangkat sembah untuk kesekian kalinya.
“Hamba,
pukulun.”
“Swarga
dan neraka sejatinya hanyalah pralambang. Kewajiban manusia sekadar menjalankan
dharma. Manakala kulup memikirkan itu, maka dharma kulup bukan tertuju kepada
Sang Pencipta, melainkan terpasung pada tujuan swarga neraka semata, tempat yang
sejatinya hanya hak Sang Hyang Tunggal untuk menetapkan penghuninya.”
Puntadewa
kembali memejamkan mata. Untuk beberapa lama, ia biarkan air mata membasahi
pipinya.
Heru Sang Mahadewa
Member
of One Day One Post


















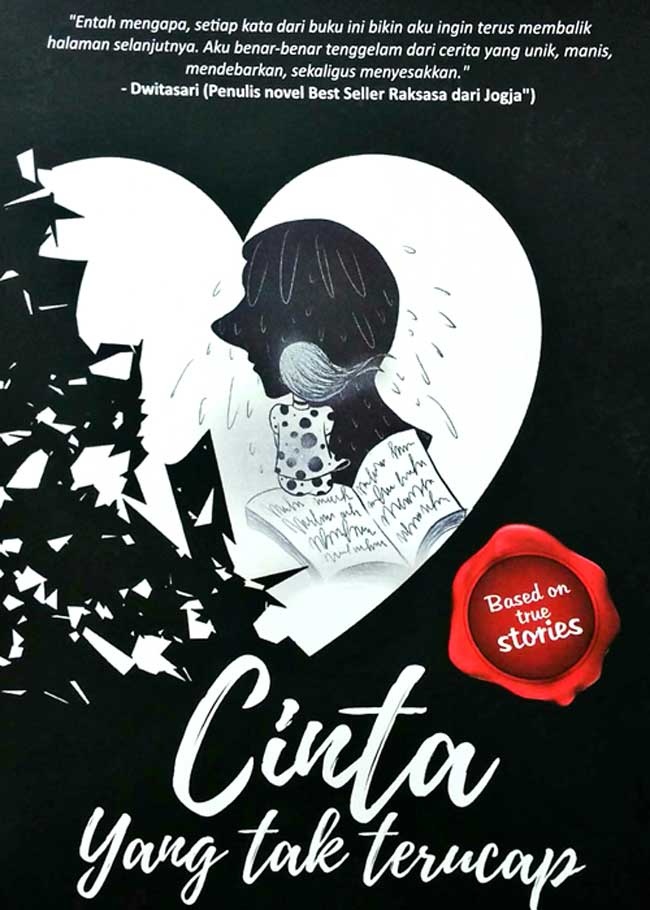
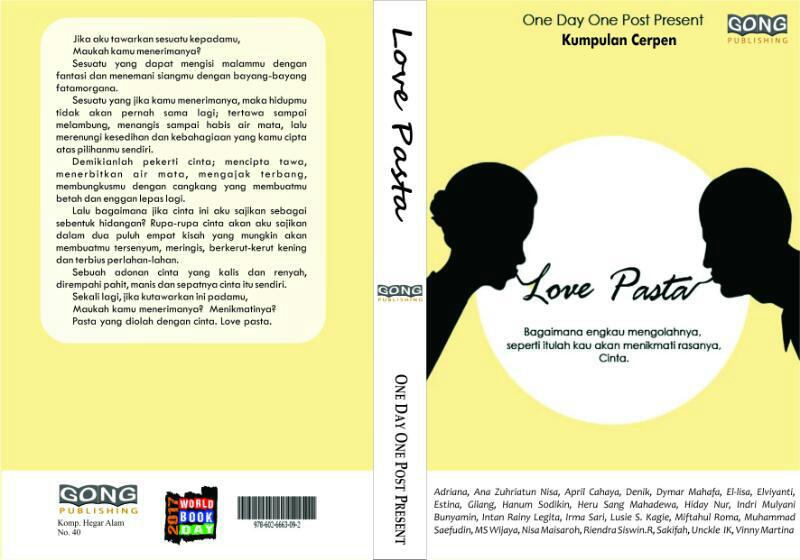
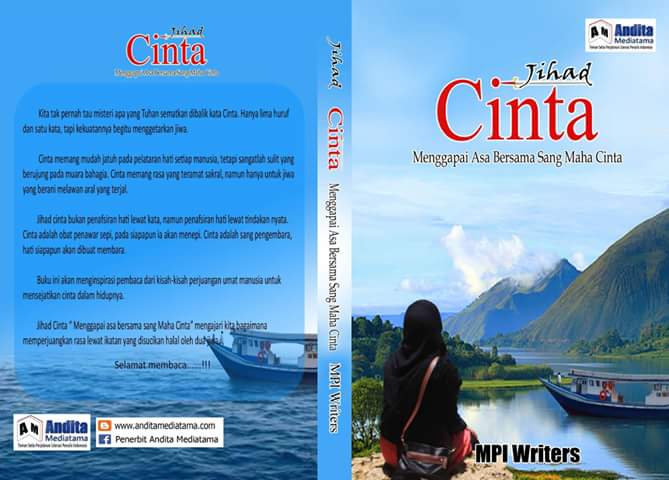
Tulisan mas heru mah selalu membuat saya kagum. Saya yang minim pengetahuan tentang dunia perwayangan jadi bisa belajar dari tulisan mas.
BalasHapus