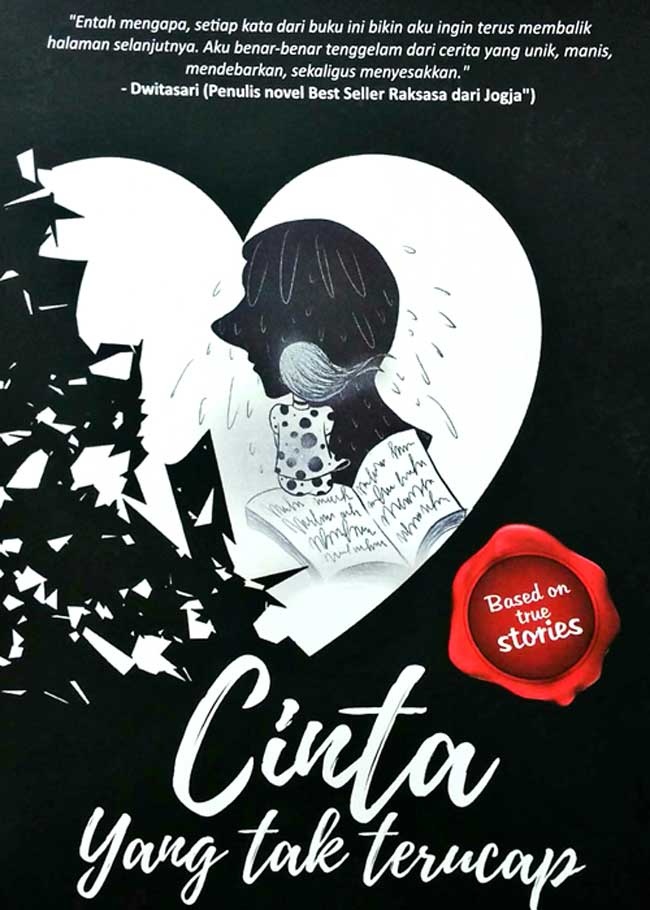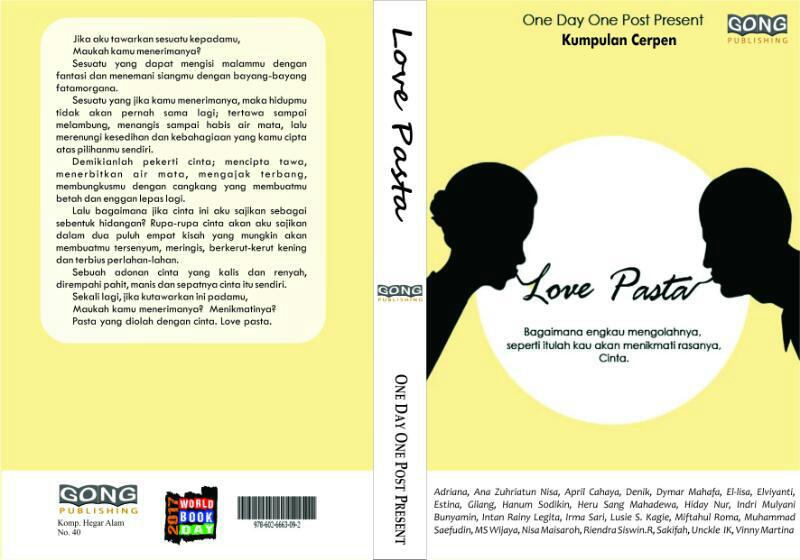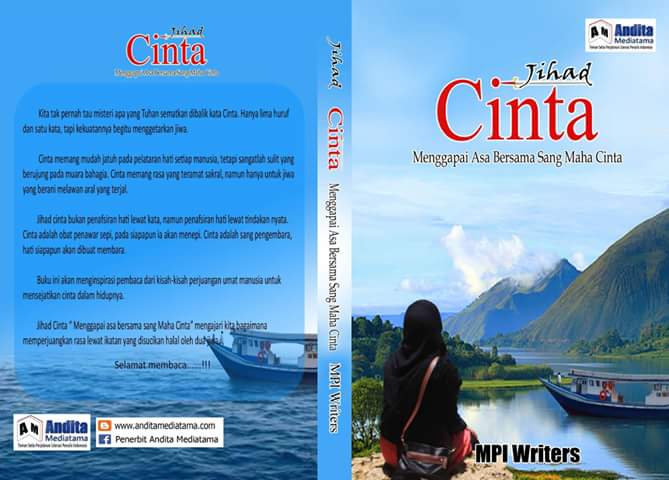Pilihan Kunti, Gandhari, dan Dristaratra untuk menghabiskan
sisa hidup dengan menjadi sunyasa di hutan Jamurdipa, berakhir dengan
dilalapnya tubuh ketiganya oleh kobaran api yang menghanguskan pertapaan
mereka. Istri, ipar, dan saudara mendiang Prabhu Pandu itu sempurna menapaki
jalan mokta: menuju ke hadapan Sang Maha Suci.
Di kedhaton Hastina, Prabhu Puntadewa telah lengser
keprabon. Parikesit, cucu Arjuna, putra Abhimanyu dari wanita yang terhitung masih eyangnya: Dewi
Uttari, dinobatkan sebagai Maharaja baru. Ia menabalkan diri dengan abhiseka
Prabhu Krishna Dwipayana, menyamai abhiseka yang pernah dipakai kakek
canggahnya.
Hastina memasuki zaman baru. Zaman di mana yang menduduki
takhta bukan berasal dari dua kubu yang berseteru di Bharatayudha: Kurawa dan
Pandawa. Perang besar sesama wangsa Bharata itu telah lama berakhir. Satu demi satu, kesatria yang dulu pernah
berjuang hidup mati di tegal Kuru Setra, kini telah tiada. Warta terakhir,
Prabhu Sri Bhatara Krishna juga mokta. Ia bahkan membawa seluruh bangsa Yadawa menuju alam sunyaruri.
Drupadi dan lima kesatria Pandawa telah berpamitan pula kepada Prabhu
Parikesit. Tekad untuk menghabiskan sisa umur dengan menjadi pertapa di puncak
gunung Mahameru telah bulat. Para putra Pandu dan menantunya itu ingin menebus
dosa masa lalu dengan mendekatkan diri kepada Sang Maha Pengampun.
-oo0oo-
Belantara gunung Mahameru bagai kepala Hyang Bhatara Kala.
Jurang-jurang yang menganga tak ubahnya seperti mulut Dewata penguasa waktu
itu. Tebing-tebing yang berdiri menjulang, nampak menyerupai taring-taring tajam. Sepanjang pendakian menuju puncaknya, Drupadi, Puntadewa, Wrekudara, Arjuna,
Nakula, dan Sadewa berjalan tertatih-tatih dengan sisa tenaga mereka yang telah renta.
Setelah berjalan selama empat hari empat puluh malam, Drupadi
ambruk. Cuaca tak menentu di dalam belantara, membuat pertahanan tubuh perempuan dari Pancali itu jebol. Ia menolak dirawat suaminya, Puntadewa. Pun demikian dengan penawaran
empat adik iparnya. Perempuan tua yang pernah ditelanjangi di Balai Manguntur
Hastina oleh Kurawa itu kukuh dengan prinsipnya bahwa Pandawa harus bisa
mencapai puncak Mahameru.
Di kaki Mahameru, suksma Drupadi melesat meninggalkan raga,
sebelum mencapai swargaloka di dataran tertinggi gunung itu.
Pendakian Pandawa berlanjut. Putra-putra Kunti dan Madrim
menghadapi ujian yang kian berat.
Malam ke empat puluh satu, hujan disertai ulur-ulur menghajar
gunung Mahameru. Kabut tebal juga membekap setiap jengkal rimba. Sadewa terperosok ke jurang sedalam lima ratus tombak.
Tubuhnya yang ringkih meluncur ke bawah, hancur menimpa bebatuan di dasarnya.
Pun demikian dengan Nakula yang nekad menyelamatkan dengan terjun menyusul:
ikut berpulang bersama kembarannya.
Puncak gunung Mahameru masih separuh perjalanan. Tekad
Puntadewa, Arjuna, dan Wrekudara belum meredup. Kedhaton Bathara Indra ada di atas sana. Kedhaton yang dipercaya menjadi pintu gerbang menuju swarga. Dengan sisa
tenaga yang kian rapuh, mereka kembali merangkak, menapaki tebing demi tebing.
Nahas, Arjuna ambruk pula pada malam ke empat puluh lima. Segala
kedigdayaan di masa muda pemilik panah Pasoepati itu seakan tak berarti lagi.
Jauh sebelum menginjakkan kaki di gerbang kedhaton Bhatara
Indra, suksma lelanange jagad itu menyusul kedua adiknya.
Wrekudara berontak!
Ia tidak terima dengan amukan semesta alam. Kematian
Drupadi, Sadewa, Nakula, dan terakhir Arjuna, menurutnya adalah ulah alam yang
tidak bersahabat dengan Pandawa.
Dengan sisa-sisa tenaga tuanya, ia menggunakan
kekuatan Blabag Panganthol-anthol untuk merobohkan pepohonan untuk membalas rasa sakit hatinya.
Batu-batu berukuran besar juga ia coba hancurkan. Namun, kekuatannya hanyalah tinggal kekuatan manusia
yang telah ringkih dimakan usia. Tubuh Wrekudara justru terpelanting karena
tidak mampu mengendalikan dahsyatnya ajian yang diterima dari ruh Kumbakarna itu, hingga ia terperosok ke jurang pula.
Kini, yang tersisa hanya Puntadewa.
Ayah dari Pancawala itu nyaris putus asa. Tekad untuk
mendaki ke puncak Mahameru ia urungkan. Pada sebatang pohon randu alas, ia sandarkan
tubuhnya. Pupus sudah niatan untuk mokta bersama istri dan keempat adiknya.
Dalam keputus-asaan yang nyaris mengantarnya ke jalan belapati, Puntadewa
dikejutkan lolongan Segawon Lanang, seekor anjing jantan piaraannya. Ia baru sadar, telah melupakan keberadaan binatang itu. Binatang yang menyertai
perjalanan Drupadi dan Pandawa sejak dari Hastina hingga kini sampai di lereng Mahameru.
Segawon Lanang berlari-lari kecil menapaki
tanjakan demi tanjakan. Anjing berbulu coklat itu terus meninggalkan Puntadewa.
Sesekali binatang itu berhenti, lalu menoleh ke arah Puntadewa sambil mengibaskan ekornya.
Puntadewa beranjak dari pohon randu alas. Ia bisa menangkap bahasa
tubuh Segawon Lanang. Kini, niat untuk menyelesaikan pendakian menuju puncak Mahameru
tumbuh kembali.
Anjing piaraan itu seolah memberinya pesan: meski
Drupadi dan keempat adiknya telah mendahului pergi, Puntadewa harus tetap melanjutkan
pendakian. Bersama anjing itulah, ia pupuskan duka di hatinya dengan melantunlangitkan
mantra puja-puja kepada Hyang Jagad Nata.
Puntadewa terus mendaki, hingga malam ke delapan
puluh, ia sampai di sebuah hamparan tegal nan luas. Di hadapannya, terbentang nyala yang terang benderang. Nyala api kebenaran. Nyala yang menerangi jalan pada malam itu. Sementara di kanan kiri
jalan itu, tebing dan jurang nampak menganga dalam balutan kegelapan.
Dengan kilauan nyala api kebenaran itu pula, kini Puntadewa bisa membedakan dengan jelas: mana kegelapan,
mana bayangan, dan mana jalan sejati.
Puntadewa terus berjalan, ditemani anjing setia yang tak pernah selangkahpun menjauh dari sisinya.
Akhirnya ia tiba di pintu gerbang swarga dan
disambut Bhatara Indra yang mempersilakannya naik ke atas sebuah kereta kencana. Namun, ketika Puntadewa hendak menggendong Segawon Lanang, justru perkataan Bhatara Indra sungguh di luar dugaannya.
"Tidak ada tempat bagi anjing di swarga," ucap Bhatara Indra.
"Kalau
begitu, tidak ada tempat pula bagiku di swarga. Aku tidak mungkin
meninggalkan anjing yang telah setia menemaniku sejak dari Hastina hingga ke
puncak Mahameru ini dalam suka maupun duka," sanggah Puntadewa.
Sejurus kemudian, Puntadewa turun dari
kereta bersama anjing piaraannya.
Bhatara
Indra memuji jawaban Puntadewa. Bagi Dewata penguasa langit dan gunung
itu, Puntadewa telah menunjukkan kasih sayang, kesetiaan, dan
penghargaan kepada teman hidupnya, meskipun hanya seekor anjing.
Bhatara Indra mempersilakan Puntadewa kembali naik
ke kereta kencana. Kali ini, Segawon Lanang diizinkan ikut. Begitu naik ke kereta,
anjing itu lenyap.
“Ketahuilah, kulup. Anjing itu sesungguhnya adalah
penyamaran dari Bhatara Dharma.”
Puntadewa memasuki swarga dengan dituntun Bhatara
Indra.
(Heru
Sang Mahadewa)
Member of One Day One Post
#30DWC
Sumber gambar: album wayang Indonesia